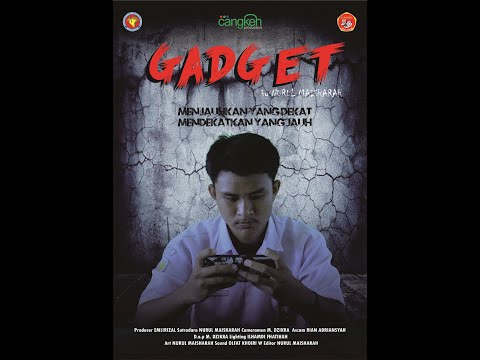| Berita / Pameran |
Dari Realisme Hingga Religiusitas
| Oleh Erianto | ||
| ||
| Kini, kiranya memang sudah tidak perlu dipersoalkan lagi apakah seorang seniman (pelukis) akan melukis dengan gaya, bahan, teknik atau tema apapun yang dia ingini. Juga tidak perlu diragukan lagi, bahwa semua gaya mendapat tempat yang sama dalam dunia seni lukis. Ungkapan yang mengatakan bahwa sebuah gaya adalah dasar bagi gaya yang lain, atau gaya tertentu lebih tinggi nilainya dibanding gaya yang lain, mungkin sudah tidak relevan lagi. Singkatnya, hiruk pikuk segala wacana seputar masalah aliran (isme) tidak perlu harus membayang-bayangi konsentrasi dan mood seorang pelukis dalam perjalanan kreatifnya.
Mikke Susanto pernah menulis bahwa masalah aliran dan gaya tidak lagi menjadi dominasi penting dalam pembicaraan seni rupa., bahkan dinilai sebagai sisa-sisa kepingan masa lalu yang sudah berubah makna dan tujuannya. Dengan menggunakan gaya dan aliran sebagai alat pembanding antar seniman dan karyanya, pembicaraaan seni rupa cendrung terjebak hanya sebagai kegiatan golong-menggolongkan semata, sedangkan kegiatan apresiasi yang sesungguhnya cendrung terabaikan. Karena itu, kini gaya dan aliran hanyalah sebagai penanda dan alat saja, bukan sebagai tujuan pencarian makna dan identitas yang sesungguhnya. Setiap seniman harus menemukan keunikannya sendiri, yang tentu saja tidak bisa dibatasi hanya oleh frame aliran yang sudah ada.1 Lebih jauh, dengan mengutip Suwarno, seni rupa masa kini sering disebut dengan istilah anything goes, atau meminjam istilah Arthur Danto, sudah berada dalam kondisi the end of art. Artinya pemikiran dan gubahan karya seni kini sudah tergantung pada senimannya, mau dianggap sebagai apa: sebagai karya seni atau bukan dan sebagainya. Akibatnya, eksplorasi dan berbagai kemungkinan terbuka ke segala arah. Segalanya menjadi boleh: proses penciptaan, material, media, teknik, gaya dan segala totalitasnya meluncur tanpa batas.2 Praktek seni dengan inovasi inovasi baru terus berlangsung bahkan mengalir deras, sementara di sisi lain upaya pemaknaan terhadap karya-karya semakin hari semakin tertinggal. Artinya laju perkembangan pemaknaan dengan kemunculan karya-karya baru tidak lagi seimbang, melainkan dalam rentang percepatan yang nyaris tidak terikuti. Karena itu tidak mungkin lagi ada otoritas yang berhak mengklaim pemaknaan seni secara tunggal. Segalanya sudah terdesentralisasi, pecah menyebar tanpa standar yang bisa mengeneralisir semua jenis karya dan pemaknaan. Inilah sebuah fase, yang menurut Lyotard, dimana logika tunggal yang dianut oleh kaum modernis sudah mati digantikan oleh pluralitas logika atau paralogi. Dalam bahasa yang agak provokatif, Lyotard menulis: .....mari lawan totalitas, .... dan hargailah perbedaan.3 Dengan semangat inilah Pameran Lukisan yang bertema Dari Realisme hingga Religiusitas ini diberlangsungkan, bukan dalam rangka membunuh atau membangkitkan kembali wacana seputar aliran dalam seni rupa, melainkan sebuah ikhtiar dalam merayakan keragaman. Menyebutkan kata realisme dan religiusitas misalnya, hanya dimaksudkan sebagai pemetaan dan penamaan yang memudahkan pemahaman kita, bukan sebagai nama yang bersifat mutlak apalagi menyandang sakralitas sebuah gaya. Dengan tema Realisme hingga Religiusitas, pameran ini ingin menyerukan semangat pembebasan dari hegemoni gaya tertentu, semacam jembatan lintas mazhab yang mengakui pluralitas gaya dalam seni rupa. Artinya, pameran ini ingin menepis adanya stratafikasi diantara bebagai gaya yang ada. Setiap gaya hanyalah masalah pilihan bahasa ungkap. Karena itu, keragaman gaya ke lima pelukis ini (Evelyna Dianita, Herisman Tojes, Irwandi, Iswandi dan Nasrul) tidak menjadi halangan untuk ditampilkan dalam satu paket pameran, justru keragaman ini menjadi kekayaan kreatifvitas yang mereka miliki bersama. Bila kita simak, perjalanan berkesenian kelima pelukis ini sudah cukup panjang, namun sejak tahun 2000 semakin menunjukkan kiprah seni lukisnya sejalan dengan kemunculan Sarasah Art Gallery di Padang, dimana kehadiran gallery ini ikut memicu intensitas pameran dan kemunculan pelukis-pelukis muda di Sumatera Barat, dan 2 orang diantara kelima pelukis ini (Evelyna Dianita dan Herisman Tojes) termasuk yang ikut menggagas kelahiran galeri tersebut. Seiring dengan itu, kelima pelukis ini semakin sering pameran ke beberapa kota baik di Sumatera maupun Jawa. Beberapa orang diantara mereka merupakan peraih berbagai prestasi pada event-event seni lukis tingkat Sumatera dan Nasional (Peksiminas, Pameran seni Lukis Karya Terpilih Se-Sumatera, Pameran Karya Terpilih Nusantara dan Indofood Art Awards) dan beberapa prestasi dalam bidang keseni-rupaan lainnya, seperti dapat kita lihat pada biodata masing-masing pelukis. Menurut pemetaan Suwarno, nama-nama pelukis ini tergolong sebagai generasi era Kontemporer dalam sejarah seni rupa Sumatera Barat (Minang).4 Sementara bagi Ady Rosa dalam pengantar Kurasinya pada Pameran Pentagona di Bumi Minang Padang tahun 2003, dimana Herrisman Tojes dan Irwandi termasuk sebagai peserta, termasuk sederet nama-nama pelukis yang segenerasi merupakan fase ketiga dalam sejarah seni lukis Sumatera Barat setelah era Wakidi (1890-1987) dan kelompok SEMI (Seniman Muda Indonesia - 1947) yang didirikan oleh A.A Navis dan kawan-kawan di Bukittinggi.5 Singkatnya, meminjam istilah budayawan Umar Kayam, kiprah seni lukis kelompok ForT de Kock ini bukanlah tergolong seniman dalam rangka, yang melukis hanya karena akan pameran. Kelima pelukis ini memang sudah menunjukkan aktifitas berkeseniannya secara intens. Pameran yang diadakan di Bukittinggi ini, seperti yang dituturkan kelompok ini dalam pengantarnya, lebih merupakan suatu panggilan, semacam dakwah apresiasi melalui karya-karya yang ditampilkan, sehingga diharapkan terjadi proses perluasan medan berkesenian yang tidak hanya terkonsentrasi pada kota-kota tertentu di Sumatera Barat (seperti Padang). Apalagi dalam sejarah seni rupa Sumtera Barat, Bukittinggi termasuk basis kelahiran sekolah seni rupa (Kweek School) yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1856 dengan gurunya Van Dijk, yang kemudian melahirkan pelukis maestro Wakidi (1890-1979).7 Selain itu juga, mengingat Bukittinggi sebagai kota wisata, dimana seni rupa termasuk aset budaya dalam komponen pariwisata, diharapkan pameran ini dapat menjadi investasi budaya dalam membangun infrastrukutur kesenian di Bukittinggi. Kemudian pemilihan istilah Fort de Cock bagi kelompok ini bukan dalam arti membesarkan semangat kedaerahan apalagi diskriminasi wilayah, tetapi lebih sebagai simbol atau benteng yang mengikat emosional mereka karena sama-sama dilahirkan dan dibesarkan di Bukittinggi. Meskipun telah mengalami pasang surut, ternyata seni lukis bercorak realis hingga kini tetap bertahan. Menurut Mamannoor, hampir satu setengah abad sejak kemunculannya (1845) di Barat, lukisan realis terus hadir berulang bagaikan siklus yang menggelinding dalam bentangan sejarah seni rupa, termasuk di Indonesia.8 Beberapa tahun terakhir, di Indonesia (atau Sumatera Barat khususnya) kebangkitan seni lukis realis ini tampak semakin marak, meskipun tidak melulu beraroma mooi inde. Gejala ini terasa dengan sering munculnya pameran lukisan realis kembali beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pelukis yang meneruskan melukis ala wakidi (Wakidian) pun hingga kini tetap menunjukkan eksistensinya (Idran Wakidi, AR. Nizar, Firman Ismailk, Yose Rizal, dan lain-lain). Bahkan belakangan ini ada semangat baru bagi beberapa pelukis Sumatera Barat (yang biasanya agak alergi dengan lukisan realis) kini berbondong-bondong ingin melukis bergaya realis, meskipun dalam rangka studi atau pun sekedar sebagai tamasya kreativitas. | ||
| Berita Pameran Lainnya | ||
|